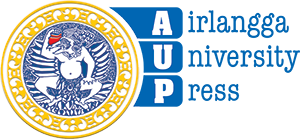PERUBAHAN BUDAYA DI INDONESIA: PERSPEKTIF SEJARAH, LINGUISTIK, DAN SASTRA
Keywords:
Indonesia, Sejarah, Sastra, LinguistikSynopsis
Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah lagu qasidah lama yang dinyanyikan oleh sebuah grup qasidah yang sangat tenar pada tahun 1980-an, Nasida Ria. Lagu tersebut berjudul Tahun 2000, sebuah lagu yang menggambarkan bahwa tahun 2000 kita akan memasuki zaman mesin di mana manusia digantikan oleh mesin. Saya terhenyak mendengar lagu yang diciptakan tahun 1982, karena ternyata merupakan sebuah “ramalan” yang kemudian terbukti benar.
Mesin benar-benar telah menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan kehidupan manusia pada saat ini. Nasida Ria dalam salah satu baitnya menuliskan bahwa: …“Tahun dua ribu kerja serbamesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin.” Manusia tahun 2000 yang menklaim dirinya sebagai menusia modern hidup dilayani oleh mesin mulai bangun pagi sampai tidur lagi di malam hari. Bahkan dalam tidur pun banyak manusia ditemani oleh mesin, yaitu hand phone.
Modernisasi telah menyerat manusia menjadi bagian dari mesin, bukan sebaliknya. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap mesin pelan-pelan “mengenyahkan” eksistensi manusia sebagai mahluk pekerja dan pemikir. Sebagian besar keinginan manusia saat ini bisa diwujudkan hanya dengan sentuhan sebagian kecil anggota tubuh serta sebagian kecil pikiran. Definisi kerja suatu saat harus diubah seiring dengan perubahan teknis apa yang dimaksud kerja itu sendiri. Mesin telah mengenyahkan sebagian besar definisi manusia sebagaimana didefinisikan para ahli di masa lampau.
Perubahan radikal yang terjadi pada manusia tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu humaniora. Manusia yang tidak siap menghadapi perubahan atau bahkan menolaknya akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Problem kemanusiaan akan semakin mencuat yang perlu mendapatkan perhatian para ilmuwan humaniora. Ilmuwan akan menghadapi dua hal, pertama, berbagai perubahan yang bisa diamati dan menjadi bahan kajian serta diubah menjadi ilmu pengetahuan. Kedua, berbagai problem yang dihadapi oleh manusia yang perlu mendapatkan penanganan secara praksis.
Buku ini lahir berkat pengamatan jeli yang dilakukan oleh para ilmuwan yang tergabung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Mereka adalah para guru besar yang pekerjaan sehari-harinya meneliti di lapangan dan mengajar di kelas. Berbagai tema yang ditulis di buku mengacu kepada beragam persoalan yang melanda manusia dalam merespon perubahan atau problem yang dihadapinya. Terdapat tujuh tulisan dengan tema beragam, mulai dari sejarah, linguistik, dan sastra.
Selama ini ilmu humaniora dipandang sebagai ilmu yang kurang memiliki kegunaan praktis karena sifat ilmunya yang hanya menyodorkan hal-hal yang bersifat imaterial. Pandangan semacam itu bisa berubah manakala kita membaca tulisan di buku ini. Gagasan dalam lingkup ilmu humaniora memang tidak seperti ilmu teknik yang memberi petunjuk mengenai bagaimana caranya sebuah palu digunakan, tetapi ilmu humaniora memberikan gagasan mengapa sebuah palu perlu dibuat. Ilmu humaniora menawarkan ide yang pas agar sebuah benda bisa digunakan dengan tepat untuk kepentingan yang membuat manusia lebih bijak dan manusiawi. Sebuah palu tanpa didampingi ilmu humaniora bisa disalahgunakan untuk memukul kepala manusia. Dengan ilmu humaniora, sebuah palu hanya dimanfaatkan untuk membangun rumah yang membuat penghuninya merasa nyaman, tanpa takut rumahnya roboh karena telah tersambung oleh pasak-pasak yang dipukul keras oleh sebuah palu.
Buku ini merupakan kumpulan naskah pidato pengukuhan jabatan Profesor/Guru Besar, yang dibacakan di depan Rapat Universitas Airlangga. Naskah pertama ditulis oleh Purnawan Basundoro ketika pandemi Covid-19 sedang tinggi-tingginya melanda dunia. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah ilmu sejarah bisa ikut berkontribusi mengatasi pandemi yang tengah menggila? Basundoro yang ahli sejarah perkotaan menyodorkan argumen bahwa dengan belajar pada sejarah maka manusia akan mendapatkan bekal untuk menghadapi problem yang menghadang mereka. Pandemi bukan hal pertama yang melanda dunia. Menjalarnya Covid-19 tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan mesin yang telah mempermudah moblitas manusia. Penemuan manusia atas mesin-mesin transportasi telah mempercepat interaksi manusia dari berbagai belahan dunia.
Pada awal abad ke-20, dunia dilanda pandemi Flu Spanyol yang sumbernya berasal dari Amerika Serikat. Pengiriman tentara ke negara-negara Eropa telah menyebabkan Flu Spanyol menyebar ke benua tersebut, dan dari situ menyebar ke kawasan Asia termasuk Indonesia. Mesin-mesin kapal telah mempercepat penularan penyakit ke seluruh dunia, karena interaksi antar manusia menjadi sangat mudah. Penularan penyakit disebabkan karena interaksi yang intens antar inang, yaitu manusia. Hal yang sama terjadi pada penularan virus Covid-19 yang terjadi pada dekade kedua abad ke-21. Mesin-mesin pesawat terbang menjadi kontributor utama dalam penyebaran virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan Tiongkok.
Belajar dari sejarah pandemi Flu Spanyol yang terjadi seratus tahun sebelumnya, Basundoro yang cukup memahami karakteristik ruang dan manusia penghuni ruang perkotaan menawarkan solusi agar dilakukan rekayasa terhadap ruang perkotaan. Ruang-ruang harus diubah sedemikian rupa selama masa pandemi agar intensitas interaksi antar manusia berkurang. Dengan demikian pelan-pelan penyebaran virus juga akan melambat.
Naskah kedua ditulis oleh Sarkawi B. Husain, menyoroti Kota Surabaya sebagai kota pergerakan dan kota revolusi. Surabaya telah lama mendapat julukan kota pahlawan, mengacu kepada perang besar antara rakyat Surabaya beserta seluruh unsurnya melawan tentara Sekutu, yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, sebagai simbol bersatunya rakyat dalam melawan segala bentuk penjajahan. Melalui perang tersebut bangsa Indonesia secara keseluruhan terwakili untuk memperlihatkan kepada pihak manapun, bahwa jika berani menjajah Indonesia makan akan mendapatkan konsekuensi seperti tentara Sekutu Inggris yang dilawan mati-matian oleh rakyat Surabaya.
Melalui naskah yang ditulisnya, Husain juga memperlihatkan bahwa jauh sebelum meletus perang 10 November, Surabaya telah menjadi episentrum perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Awal abad ke-20, Surabaya telah berkembang menjadi kota pergerakan dengan beberapa tokoh sentralnya, yaitu H.O.S Tjokroaminoto dan dr. Soetomo. Kedua tokoh tersebut berhasil menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan kolonilisme Belanda secara lebih terstruktur dan masif menggunakan organisasi modern. Tjokroaminoto melakukan perlawanan dengan menggunakan organisasi Sarekat Islam, sedang Soetomo melakukan hal yang sama melalui organisasi Budi Utomo. Saat tinggal di Kota Surabaya ia mendirikan Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studieslub), yang kemudian diubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI) pada tahun 1930. PBI kemudian mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1935.
Tjokroaminoto dan Soetomo telah memperlihatkan perlawanan yang berbeda dengan periode sebelumnya. Mereka memiliki spektrum dan pengaruh yang sangat luas, dengan memanfaatkan politik dan organisasi sebagai alat perjuangan. Surabaya menjadi salah satu kiblat pergerakan pada masa itu, bersambung menjadi pelopor perlawanan bersenjata pada masa revolusi. Sayangnya, kesadaran bersejarah masyarakat dan pemerintah kota kadang naik turun. Husain bahkan menganggap bahwa ada amnesia sejarah di Surabaya. Hal itu bisa dicegah dengan cara terus-menerus belajar sejarah serta merawat peninggalannya.
Naskah ketiga menyoroti tentang kritik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, ditulis oleh Edy Jauhari yang merupakan ahli dalam bidang linguistik pragmatik. Kritik tentu saja bukan hal asing bagi masyarakat Indonesia, tetapi bukan berarti tanpa masalah tentang hal tersebut. Masyarakat Indonesia secara umum bukanlah masyarakat yang mau menerima kritik yang dilakukan secara terbuka. Budaya feodal yang masih sangat kuat menyebabkan hal tersebut. Banyak orang menjadi sakit hati karena dikiritik oleh orang lain, bahkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan tidak segan-segan untuk memenjarakan orang yang mengritiknya. Dalam politik kontemporer Indonesia yang selalu didengungkan sebagai politik demokratis ternyata enggan menerima kritik. Budaya Jawa mengenal istilah ngono yo ngono, tapi mbok ojo ngono.
Jauhari mengamati fenomena tersebut berdasarkan ilmu linguistik. Kritik yang dilontarkan oleh seseorang kadang ditafsirkan berbeda, dsn dianggap sebagai penghinaan, ujaran kebencian, penistaan, atau bahkan fitnah. Inilah yang menyebabkan seseorang terancam masuk penjara gara-gara melontarkan sebuah kritik, terutama jika hal tersebut diarahkan kepada lawan politik. Tulisan Jauhari mencoba menjelaskan dari perspektif linguistik pragmatik apa sesungguhnya kritik itu, apa fungsinya, dan apa perbedaannya dengan ungkapan-ungkapan lain yang sering dikategorikan sebagai kekerasan verbal (menghina, memaki, mencaci, menista,dan sejenisnya).
Pemikiran yang ditulis oleh Jauhari sangat relevan dengan situasi saat ini, ketika kondisi politik Indonesia bersandingan dengan kemudahan seseorang melontarkan kritik melalui berbagai media. Kita berkewajiban untuk membangun demokrasi yang sehat, yang dilandasi dengan kritik, sehingga jangan sampai kritik dianggap sebagai hinaan. Kritik harus diposisikan sebagai bagian untuk memperkuat demokrasi. Oleh karena itu agar kritik tepat sasaran dan tidak ditafsirkan sebagai instrumen penyerang, harus ada tata cara dan etika kritik. Jauhari menawarkan cara mengkritik berdasarkan prinsip-prinsip ilmu linguistik pragmatik yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi perbedaan tafsir terhadap makna kritik.
Naskah keempat ditulis oleh Ni Wayan Sartini. Beliau selama ini banyak meneliti bahasa daerah, khususnya bahasa Bali. Naskah yang ia tulis menyoroti fungsi ritual pertanian sebagai media untuk pelestarian bahasa Bali. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan bahasa daerah, mengacu kepada banyaknya etnis yang ada, karena hampir semua etnis memiliki bahasa sendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sayangnya bahasa daerah berada di ambang kekritisan berhadapan dengan bahasa nasional dan bahasa global. Namun demikian di beberapa daerah terhadap kearifan lokal mengenai bagaimana caranya agar bahasa setempat tidak benar-benar tersapu bersih oleh arus modernisasi.
Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah yang juga kena dampak aruas globalisasi dan modernisasi. Banyak kosa kata dalam bahasa Bali keberadaannya semakin memudar karena semakin jarang digunakan. Adanya pergeseran penggunaan bahasa daerah membuat eksistensi bahasa Bali semakin berkurang terutama pada anak-anak muda. Kondisi semacam itu cukup mengkhawatirkan, sehingga perlu upaya keras agar bahasa Bali tetapi bisa bertahan. Salah satu upaya mempertahankan bahasa daerah Bali adalah melalui ritual pertanian.
Berdasarkan pengamatan Sartini, ritual pertanian ternyata menjadi sarana efektif untuk pelestarian bahasa Bali. Ritual pertanian di Bali hampir semuanya dilakukan dengan menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa pengantar doa, syukur, dan harapan. Memang ritual pertanian tidak bisa melestarikan seluruh unsur bahasa Bali karena cakupannya yang terbatas, namun demikian paling tidak terdapat kosa kata tertentu bisa bertahan karena terus-menerus dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut.
Diah Ariani Arimbi menulis naskah dengan tema tentang dunia perempuan dalam kebudayaan. Ia berangkat dari pemikiran bahwa dalam konteks budaya Indonesia yang patriarki, perempuan sering mendapatkan ketidakadilan. Prinsip-prinsip yang mengatur relasi gender sering kali menempatkan kekuasaan yang signifikan di tangan laki-laki, sehingga secara efektif meminggirkan otonomi perempuan. Salah satu hal yang sering menjadi permasalahan terkait relasi laki-laki dan perempuan adalah hak reproduksi.
Penyangkalan atas kepemilikan tubuh dan hak reproduksi merupakan permasalahan yang meluas; ketika perempuan mencoba untuk menegaskan kendali atas keputusan reproduksi mereka, hal itu sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap norma dominasi laki-laki yang sudah tertanam. Perjuangan perempuan untuk memperoleh otonomi ini bukan hanya persoalan individu tetapi juga isu sosial yang lebih luas, karena kemampuan perempuan dalam mengelola kesehatan reproduksi mereka secara langsung memengaruhi kapasitas mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri dan menjadi tantangan terhadap struktur patriarki yang sudah tertanam.
Persoalan tubuh perempuan salah satunya tergambar dalam karya-karya sastra yang terbit dalam berbagai tahun di Indonesia. Karya sastra secara umum adalah gambaran mengenai realitas yang sesungguhnya yang berkembang di masyarakat. Budaya Indonesia yang secara umum masih mengistimewakan sosok laki-laki menjadikan posisi perempuan Indonesia masih lemah dalam berbagai bidang kehidupan. Pelecehan seksual menjadi salah satu hal yang masih mencuat di mana-mana.
Penekanan berlebihan pada penampilan fisik juga dapat mengesampingkan kualitas berharga lainnya, seperti kecerdasan, bakat, dan karakter. Dinamika budaya ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melanggengkan narasi sosial yang lebih menghargai kesesuaian dibandingkan keaslian. Perlu perjuangan bersama untuk menempatkan perempuan secara proporsional agar lebih berdaya dan setara dengan laki-laki. Kita harus secara aktif berupaya menciptakan kondisi yang mendorong keadilan dan kesetaraan bagi semua individu.
Berkebalikan dengan tema yang ditulis oleh Arimbi, Nur Wulan dalam naskah keenam di buku ini membahas mengenai maskulinitas atau norma kelelakian. Ia berangkat dari pemikiran bahwa selama ini studi tentang gender di Indonesia masih didominasi oleh kajian tentang perempuan dan norma keperempuanan, sebagaimana dibahas oleh Arimbi. Sampai saat ini jurnal serta berbagai penerbitan mengenai perempuan sudah relatif banyak, tetapi jurnal yang membahas mengenai laki-laki an maskulinitas nyaris tidak ada. Di perguruan tinggi, program studi yang khusus mengkaji tentang laki-laki dan maskulinitas, sampai saat ini belum ada. Hal ini tentu saja membuat perdebatan dan diskusi tentang kesetaraan jender menjadi kurang adil.
Kajian tentang maskulinitas sudah berkembang di Barat dan menghasilkan banyak teori. Realitas dunia norma kelelakian Barat dan Indonesia tentu saja sangat berbeda, sehingga teori yang dihasilkan oleh para ahli dari sana menurut Nur Wulan agak kurang pas untuk membedah maskulinitas di sini. Para ahli Indonesia diharapkan melakukan kajian sendiri mengenai tema ini sehingga dapat menghasilkan teori yang sesuai dengan budaya setempat.
Kesetaraan jender hanya bisa tercipta dengan adanya peran aktif antara kedua belah pihak, perempuan dan laki-laki, oleh karena isu kesetaraan jender jangan hanya ditujukan kepada kaum perempuan. Nur Wulan menawarka gagasan agar kajian mengenai posisi laki-laki harus menjadi perhatian juga supaya kesadaran mengenai hal dimaksud bisa berimbang. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki dituntut untuk berlaku sesuai ekspektasi gender yang diharapkan, misalnya kuat secara fisik dan mental, berani, pencari nafkah utama, dan sebagainya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, perlu dipelajari secara lebih mendalam tentang apa makna atau arti menjadi laki-laki Indonesia. Hal ini penting sebagai salah satu upaya untuk mengukuhkan jati diri laki-laki Indonesia.
Buku ini ditutup dengan tulisan yang dibuat oleh almarhum Ida Bagus Putera Manuaba. Beliau adalah Profesor pertama di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, teladan bagi dosen yang lain. Manuaba adalah seorang ilmuwan yang sangat tekun, menghasilkan kajian yang sangat banyak dalam bentuk tulisan di jurnal dan buku, utamanya kajian mengenai sastra. Naskah yang dimuat di buku ini menyoroti peran sastra dalam pembangunan karakter dan perubahan sosial. Ia mengawali tulisannya dengan sebuah pertanyaan mengenai keilmiahan dan objektivitas hajian kajian sastra. Karya sastra adalah hasil kebudayaan yang cukup spesifik, yang merupakan hasil gabungan antara ketrampilan menulis serta imajinasi estetis (seni). Namun demikian bukan berarti sebuah karya sastra berangkat dari ruang kosong dan semata-mata imajinasi seni yang kemudian dituliskan. Menurut Manuaba, karya sastra juga melibatkan seluruh unsur yang dipahami oleh pengarang, seperti ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lain-lain, disadari atau tidak disadari.
Banyak karya sastra yang menggambarkan realitas sezaman dan historis. Pengarang seperti Umar Kayam, W.S. Rendra, N. Riantiarno, Zawawi Imron. Ahmad Tohari, menghasilkan karya yang kental dengan unsur-unsur yang menyejarah. Artinya, yang mereka ceritakan pada hakikatnya adalah realitas yang dibahasakan dengan bahasa sastra. Membaca karya sastra tidak ada bedanya dengan membaca sejarah, dengan pembaca bisa mengambil banyak pelajaran dari karya dimaksud. Pembaca bisa mendapatkan berbagai pencerahan, karena dalam sastra terlukiskan berbagai problematika dan alternatif kehidupan yang bermanfaat untuk menyikapi kehidupan yang baik dan bijak.
Manuaba juga menekankan bahwa karya sastra dapat berfungsi sebagai pembentukan karakter individu-individu dalam masyarakat. Ini terjadi karena di dalam sastra digambarkan berbagai tipologi dan karakter manusia. Karya sastra diciptakan sebagai eksternalisasi dari berbagai pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat. Melalui karya sastra manusia mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat luas, dengan demikian pembaca karya sastra pada hakikatnya adalah para manusia bijak dan tercerahkan.
Naskah yang dimuat di buku ini menggambarkan bahwa pandangan masyarakat yang menganggap ilmu humaniora tidak memiliki fungsi teknis justru keliru. Ilmu Humaniora memiliki peran penting sebagai fondasi kuat bagi siapapun yang memiliki profesi mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang bersifat teknis. Problematika manusia modern adalah keterasingan di tengah keramaian. Problem ini bukan semata-mata bersifat psikologis dan sosiologis, namun merupakan problem kemanusiaan secara umum.
Keberadaan teknologi sistem informasi dengan bantuan internet memang bisa memberi solusi untuk sementara waktu untuk manusia yang mengalami keterasingan. Mereka bisa menenggelamkan diri dalam dunia maya melalui media sosial yang sangat ramai. Namun solusi dengan cara memasuki dunia maya bukan berarti bisa menyelesaikan masalah keterasingan itu. Dampak yang ditimbulkan akibat memasuki dunia maya secara total bisa jauh lebih dahsyat dan merusak. Bencana kemanusiaan berada di depan kita, dan di sinilah ilmu humaniora harus mengambil peran untuk ikut menyelesaikan problematika manusia modern ini. Buku ini menyajikan pandangan kritis mengenai problematika yang sedang dihadapi oleh kita semua.
Downloads
References
Abrams, M. (1958). The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and. New York: Norton Library & Company.
Anderson, B. (1996). Imagined Communities: Reflections on the. London-New York: Verso.
Berger, P. L. (1991). Kabar Angin dari Langit: Makna Teologi dalam Masyarakat Modern (diterjemahkan dari buku asli A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural oleh J. B. Sudarmantao). Jakarta: LP3ES.
Berger, P. L. (1994). Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial (diterjemahkan dari buku asli Sacred Canopy oleh Hartono). Jakarta: Pustaka LP3ES.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor books Doubleday & Company.
Bourdeau, P. (1984). Language and Symbolic Power. England: Basil Blackwell.
Damono, S. D. (1984). Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Eagleton, T. (1983). Literary Theory: An Introduction. England: Basil Blackwell.

BISAC
- HIS054000 History / Social History
Published
Series
Categories
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.